Aku tak lagi melihat keindahan bulan purnama
Tetesan embun kini berwarna perak, di mataku
Rasa apa ini? Kenapa begini?
Akankah selalu begini? Aku yakin tidak akan terjawab
Aku pernah kehilangan cinta, dua kali
Dua kali juga aku pernah mati karenanya
Aku selalu berusaha bangun dan mengenyampingkan selimut derita ini
Tapi fakta ini terlalu kejam karena bukan cuma aku yang tersiksa
This story is dedicated to all beautiful people, it means all of you. Thank you for reading.
Menyeringai, semua menyeringai. Aku selalu benci tawa mereka. Tak ada satu pun ekspresiku yang mampu menghentikannya.
“Abaikan mereka”, perintah Willy. Selalu begitu. Dia selalu tahu apa yang harus kulakukan ketika kami melintas di tengah mereka. “Dengar, Jo, aku akan selalu mendukungmu.”
Aku terkadang tak tahan dengan ucapan mereka di belakang. Meski aku cinta perdamaian dan sedang berjuang untuk mewujudkannya, tapi aku tidak akan pernah berdamai dengan mereka. Tidak akan! Kupertegas itu di dalam diriku.
Karena itulah aku membiarkan mereka terus memakiku. Mereka tak pernah secara mutlak salah menilaiku. Namun jika begitu, masihkah aku layak disebut sebagai pejuang perdamaian? Perdamaian macam apa?
Namaku Jonas, mereka memanggilku Jonas Si Gila. Cacian mereka terhadapku selalu membuatku murka. Ada sejuta panggilan yang mereka berikan hingga jumlah kata makian tidak lagi sanggup disusun untukku.
Ya, terkadang aku suka dengan makian mereka. Aku suka dengan cara pandang sepihak yang mereka berikan untukku. Makian-makian itu bisa menutup segala kebenaran dalam diriku.
Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana sifat asliku, bagaimana aku menjalani hidup, dan bagaimana aku akan mewujudkan cita-citaku, termasuk Willy, sahabat dekatku.
Satu hal yang selalu mereka ketahui bagaimana aku menghadapi makian mereka: membalas makian dalam hati.
Aku seorang introvert totalis turunan ibuku. Aku pintar menjaga rahasia diriku. Aku tertutup dan tak akan pernah gampang membuka. Mungkin karena itu juga aku cuma punya Willy yang mau menjadi sahabatku.
Itu pun aku hampir saja membunuh orang ketika aku menyelamatkan Willy dari pengeroyokan saat demonstrasi besar-besaran dua tahun lalu, barulah Willy dan aku saling menganggap sahabat satu sama lain.
Kami dan beberapa pihak kontra lainnya terkepung kala itu, dan Willy benar-benar nyaris kehilangan nafasnya.
Aku dan Willy teman sejak SMA. Kami berdua pemikir radikal yang tak pernah mau mendukung golongan kiri. Kami sepakat untuk merelakan fakta sosial yang terjadi di sekitar kami karena memang tak mampu berbuat.
Kami terlalu realistis. Memang tidak benar begitu tapi tangan kami terikat. Kami tak mampu berbuat banyak untuk memperjuangkan kaum marjinal.
Mereka yang di atas terlalu kuat untuk membuatnya berada dalam satu sistem yang terkunci rapat. Tugas Willy mencari kuncinya dan tugasku membuka gemboknya.
Jika dibandingkan dengan Soe Hok Gie atau pemikir muda lainnya di setiap zaman, kami benar-benar jauh di bawah. Mereka merealisasikan pemikiran mereka, atau setidaknya mau dan mampu berjuang dengannya.
Sementara menyadari perbuatan mereka di masanya, kami malah menunggu fakta selanjutnya yang akan terjadi dan memikirkannya lagi. Terus begitu selama 4 tahun setelah kami berdua lulus SMA.
Kami terlalu takut untuk berbuat. Kami terlalu banyak berasumsi tentang hasilnya. Kami juga masih trauma dengan peristiwa dua tahun lalu. Seperti itulah sikap kami setelah menyepakati satu hasil dari diskusi panjang kami.
Mungkin kalian berpikir bahwa kisah ini terlalu berat karena ada hal politik di dalamnya. Tidak! Ini kisah cinta. Aku selalu ingat dengan kisahku ini setiap kali aku berdiri di hadapan cermin. Aku melihat refleksi diriku di dalam tetapi aku tidak pernah bisa melihatnya secara mendalam. Aku tidak bisa melihat besar cintaku di bayangannya, tentu tidak akan pernah.
Lima tahun yang lalu aku bertemu dengan Margaret. Dialah cinta pertama dan cinta seumur hidupku. Margaret oh Margaret, begitulah seruku dalam hati setiap kali menonton film drama romantis.
Aku sadar dia sudah tak lagi mencintaiku. Tapi sebenarnya aku tak pernah tahu bagaimana perasaannya saat ini kepadaku. Aku juga tidak mau tahu.
Tetapi ketika setiap kali jiwaku memanggil namanya, aku selalu ingat kenangan kami. Aku tidak yakin dia mengenang itu sekarang ini.
Pertemuanku dengannya terlalu sederhana. Aku tidak merasakan ada tentuan takdir dalam pertemuan kami. Waktu itu aku sedang sibuk menggantung salib di dinding kelas.
Aku tidak tahu berapa lama ia harus menunggu hingga aku menyelesaikan kerjaanku. Ia berdiri di belakangku dan mungkin berharap agar aku cepat-cepat selesai menggantung salib itu dengan letak yang benar.
Saat itu aku memang merasakan ada seseorang sedang berdiri di belakangku. Aku tidak menghiraukannya karena terlalu sibuk, setidaknya begitulah menurut Margaret. Hingga saat ini aku masih menyesal bila mengingat bahwa aku pernah mengabaikannya.
Setelah selesai menggantung salib berukuran sedang yang berwarna emas, aku meletakkan kaki kananku lebih dulu dan berusaha turun dari sebuah kursi berwarna cokelat gelap yang aku injak ketika menggantung salib tersebut.
Menoleh ke belakang, aku tidak terkejut melihatnya sedang berdiri diam menungguiku.
“Oh, ada apa?” tanyaku halus.
“Engga, aku cuma mau pinjem kursinya. Ngga enak gangguin kamu tadi lagi sibuk. Ntar palunya malah nyamber muka kamu.” katanya panjang lebar sambil berusaha ngelucu.
Aku tidak peduli dengan candaannya. Aku tertegun melihat kecantikannya. Siapa perempuan ini? tanyaku dalam hati kala itu.
Aku fokus pada mata dan raut wajahnya, bukan omongannya. Yang aku tangkap dari ucapannya hanyalah kursi. Aku masih belum tahu ada apa dengan kursi itu?
“Aku pinjem kursinya, boleh?” pintanya lagi.
“Oh boleh-boleh.” aku terlalu gugup dan pergi meninggalkannya.
Aku sengaja melambatkan langkah pergiku, berharap ia meminta bantuan untuk mengangkat kursi itu ke mana pun ia hendaki. Aku terlalu malu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Aku masih muda, dan pemalu.
Dugaanku berbeda. Harapanku pun tak terwujud. Ia mengangkat kursi itu seorang diri dan dengan cepat berjalan melewatiku. Aku menatap punggungnya dalam-dalam hingga ia menghilang melintas pintu kelas.
Saat itu kami seluruh siswa/i SMA Santo Fransiskus Asisi sedang melakukan kerja bakti untuk menyambut Natal di sekolah.
Momen-momen seperti itulah yang selalu membuatku bersemangat karena waktu belajar normal kami di dalam kelas selalu dihentikan untuk mempersiapkan acara-acara semacam itu di sekolah.
Tunggu dulu. Aku masih ingin menceritakan awal pertemuan kami. Ketika Margaret menghabiskan langkahnya keluar dari kelasku, kelas IPA 3, aku cepat-cepat mengintipnya lewat pintu yang sama.
Kepalaku melewati batas pintu sementara badanku secara utuh masih berada di bagian dalam kelas, aku melihat ke arah mana ia melangkah.
Aku tidak menyangka ia bisa mengangkat kursi itu sambil berjalan sejauh langkahnya menapak. Ia tak menyembunyikan kekuatannya, tidak sepertiku. Ia juga tak melihat ke belakang, tak juga sepertiku yang selalu bercermin pada masa lalu. Untuk apa pula ia menoleh ke belakang, alihku.
Aku terlalu memikirkan banyak hal, hal apapun yang mempengaruhi cara pandangku terhadap apapun. Aku sadar tapi tak pernah berusaha menyesarnya.
Aku memang begitu pikirku selalu, mencoba untuk tetap realistis. Sementara aku melamun memikirkan diriku, tak kusangka bahwa biji mataku masih mengikuti dirinya yang belum juga usai melangkah ke tujuannya. Lamunan macam apa ini?
Margaret berhenti di depan sebuah kelas yang berada tepat di seberang kelasku. Ruang kami belajar tahun itu hanya dipisahkan oleh sebuah lapangan basket dan kolam kecil yang dihias Gua Maria. Tidak terlalu jauh tapi mengapa aku tak pernah melihatnya?
Apakah karena aku terlalu sibuk mengautiskan diri atau belum takdir kami untuk bertemu? Tidak, tidak! Aku masih tak menganggap pertemuan kami ini merupakan sebuah takdir. Tapi bila pun ini takdir, mengapa baru saat itu takdir tersebut sampai?
Aku mungkin saja ingin merubah sikap dan cara pandangku terhadap dunia luar jika saja aku bertemu dengannya lebih awal sedikit saja. Oh Margaret, aku selalu menyayangkan momen singkat pertemuan kita kala itu.
Mataku terus berusaha fokus menatapnya di seberang. Ia menaiki kursi tersebut setelah meletakkannya.
Beberapa temannya mengelilinginya sambil memegang beberapa alat kebersihan seperti kemoceng bulu unggas, sapu panjang, dan semprotan busa serta kain lap untuk membersihkan sisa debu di kaca jendela yang dibersihkannya.
Beberapa di antara teman-temannya itu juga memegang hiasan Natal seperti pita renda berwarna merah kombinasi emas dan putih, hiasan Santa Claus, dan poster Natal khusus kelas mereka.
Meski jaraknya jauh aku masih bisa melihat pernak-pernik tersebut. Terutama, aku bisa melihat ikatan rapi rambut hitam mengkilapnya.
Ia sungguh cantik dari depan dan belakang, dan aku berasumsi bahwa ia juga cantik luar dan dalam. Aku langsung ingin memilikinya, tapi bagaimana?
Aku langsung memikirkannya. Bagaimana, bagaimana, dan bagaimana? Pertanyaan berlabel ‘bagaimana’ langsung menimbun pikiranku. Penuh. Langsung penuh. Aku merasakan panas di kepalaku.
Bukan berlebihan, aku memang selalu memikirkan setiap hal yang menarik bagiku hingga berlarut-larut, berlama-lama dalam lamunan bodoh. Tak terasa setengah jam dalam hidupku habis untuk memikirkannya. Itu pun karena dihentikan oleh Willy, teman baruku kala itu.
Jujur, aku tidak pernah benar-benar punya teman selama hidup hingga SMA kelas 2. Tak begitu pun Willy, ia bukan teman baikku saat itu. Ia hanyalah teman sebangku yang pendiam tapi bukan pemalu sepertiku.
Aku terkadang takjub dengan gagasan-gagasannya. Ia juga pemikir. Bedanya, ia tak pernah sungkan membagikan pemikirannya kepada siapapun termasuk kepadaku yang jelas-jelas bukan orang yang bisa dipercaya baginya.
Lamunan nikmatku untuk memiliki Margaret tetiba berhenti oleh Willy. Ia menyuruhku mengambilkan tasnya karena kakinya kotor setelah membersihkan teras kelas kami. Sementara aku, baru saja selesai menggantungkan salib di dinding kelas setelah mengepel bersih seluruh isi kelas.
Karena itulah tidak ada orang di dalam kelas selain aku yang bertugas mengepel dan menggantungkan salib, kemudian Margaret yang masuk begitu saja tanpa izin dan tanpa permintaan maaf karena memasuki kelas yang lantainya baru saja selesai kupel. Juga, baru saja selesai berangan-angan memiliki gadis cantik itu.
Ketika lamunanku berhenti, nikmatnya juga usai. Kenikmatan sesaat sama saja dengan mimpi indah yang putus tanpa pernah selesai, menurutku.
Aku melangkah ke bangku paling belakang di sebelah kiri menghadap papan tulis kelas untuk mengambilkan tas Willy. Aku menyerahkannya tanpa menunggu ucapan terima kasih atau ucapan apapun darinya.
Dia pergi setelah tanpa niat mengusir lamunan indahku tadi. Aku juga mengambil tasku yang ada di meja guru dan menduduki kursinya sambil memakai sepatuku.
Seharusnya aku menghargai kerja kerasku sendiri dengan cara memakai sepatu di luar kelas agar tidak mengotori lantai yang sudah susah payah aku bersihkan.
Melihat bekas langkah Margaret di atas lantai kelasku, aku jadi tak berniat menghargai hasil bersih-bersihku.
Yang aku pikirkan sambil mengikat talinya hanyalah ‘menghargai’ keberanian Margaret yang masuk tanpa izin dan keluar tanpa meminta maaf setelah meninggalkan jejak buram tersebut di kelas seniornya.
Setelah selesai aku melangkah keluar sambil menginjakkan kembali bekas pijakan gadis itu dengan upaya untuk melanjutkan pandanganku ke seberang.
Biji mataku mencari-cari tapi ia tak lagi di sana. Ke mana dia? Hilang!, dari pandanganku. Aku terkejut ketika sorot ujung biji mataku menangkap kursi kayu, dan ternyata dia sudah berada sangat dekat denganku.
“Ini, kak, kursinya. Makasih ya, kak.”
Aku bisa melihat senyum tulusnya. Ia tidak berbasa-basi. Ia tulus memberikannya untukku. Hanya untukku? Tentu saja tidak. Ada pergulatan di dalam diriku karena senyumannya itu, antara senyum tulus untukku atau senyum tulus hanya untukku.
Entahlah, aku malas melanjutkan pergulatan itu. Aku hanya ingin fokus melihat senyumnya. Darahku memanas, aku juga bisa melihat bahwa ia sedang menunggu respon ‘terima kasihnya’ dariku.
“Oh, iya. Sama-sama.” responku singkat. Hanya itu? Hanya itu yang bisa kulakukan? Hanya respon singkat tanpa makna mendalam? Kenapa aku terlahir seperti ini, ya Tuhan?
Aku tiba-tiba benci pada diriku sendiri. Sekali lagi aku benci tidak bisa berbuat banyak atas hal yang telah kupikirkan secara menelusuk.
Kedua kalinya aku membiarkannya pergi begitu saja. Aku berbuat tidak sopan dalam artian berbeda. Aku tidak sopan pada dua kesempatan yang telah diberikan kepadaku, bahkan aku tidak sopan kepada takdir jika memang itu takdir.
Kenapa aku tidak lahir sebagai Willy yang memiliki keberanian dan keterbukaan yang jauh lebih besar dariku? Pada saat itu juga aku bahkan berharap terlahir sebagai Satria, si brengsek yang gemar menghancurkan hati perempuan. Setidaknya dua orang tersebut tidak tolol sepertiku.
Aku mencatat dua kegagalan yang terjadi dalam waktu berdekatan tersebut sebagai kegagalan terburuk dalam hidupku. Mungkin sedikit berlebihan tapi ada hal yang bergejolak dalam diriku sehingga aku merasa demikian.
Aku bodoh, tolol, pengecut, dan pecundang. Aku memaki diriku dengan kata-kata seperti yang sering ditujukan orang-orang terhadapku.
Untuk pertama kalinya aku setuju dengan makian mereka, dan aku memutuskan untuk siap menerima makian-makian selanjutnya dengan ikhlas.
Baiklah, kataku dalam hati. Kejadian seperti ini takkan lagi terjadi. Aku siap merubah sifat dan sikapku, demi dia. Sesempit apapun jalan itu akan kulalui, segelap apapun nantinya akan kutembus demi cahayaku, yaitu dia.
Diriku yang lain memotivasi diriku yang lain. Aku sendiri tak lagi merasa ada pergulatan di dalam diriku. Kali ini mereka, yang satu membantu yang lain, bekerjasama demi dia.
Demi mendapatkan dia. Demi mendapatkan hatinya. Bekerjasama demi dia dengan cara meyakinkanku untuk berubah dan mendapatkannya.
Aku sudah melangkah dan harus tahu ke mana langkah selanjutnya yang harus kutapak. Dia, jawaban mutlak untuk saat ini.
Jawaban mutlak pertama kalinya yang aku putuskan sebagai tujuan. Aku belum yakin tapi sudah memutuskan. Dialah tujuanku untuk saat ini.
Aku tahu aku pasti akan memikirkan hal ini secara mendalam, membuang lagi beberapa jam waktu dalam hidupku untuk memikirkan caranya. Nothing will be wasted anymore!
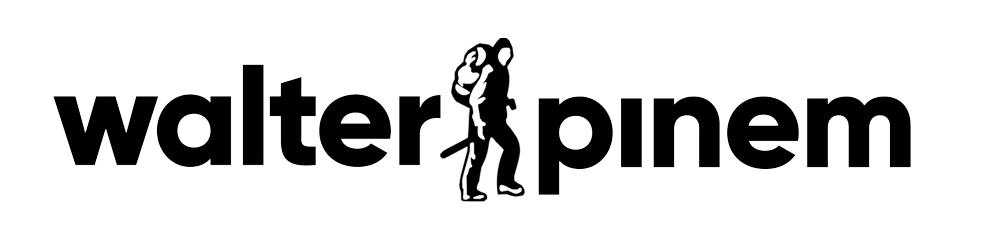




![[A Love Story] Ke Mana Langkah Selanjutnya? – Part 2](https://walterpinem.me/wp-content/uploads/2013/12/Underwater-Love-Story-6.jpg)
![[A Love Story] Ke Mana Langkah Selanjutnya? – Part 3](https://walterpinem.me/wp-content/uploads/2014/01/holding-hands.jpg)
wah. kekuatan cinta emang luar biasa ya.
bisa merubah perilaku seseorang
bagus cerpennya bro
kalau ada waktu, main ke blogku juga ya
makasih bro, segera menuju kesana 😀